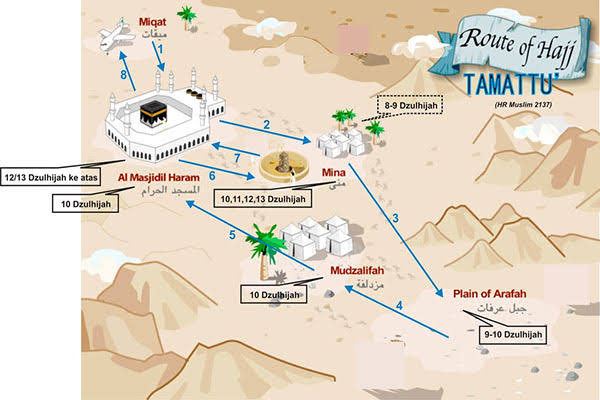TROL,- Hingga abad ke-15, tak banyak catatan tentang orang-orang Nusantara naik haji. Barulah pada abad ke-16, berbagai keterangan perjalanan haji yang dilakukan muslimin Indonesia mulai terkuak. Hal itu seiring dengan perubahan geopolitik di samudra Hindia, kawasan perairan yang menghubungkan tanah air dengan tanah suci.
M Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia menjelaskan konteks pada masa itu. Makin banyak pedagang Nusantara yang turut serta dalam pelayaran ke Asia Barat. Begitu pula para delegasi kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang menyambangi Makkah, serta para pencari ilmu yang berguru pada ulama-ulama besar di Haramain.
Pada waktu bersamaan, bangsa Barat, terutama Portugis, mengawali penjelajahannya ke Nusantara melalui samudra Hindia.
Kesultanan Turki sebagai kekuatan baru Dunia Islam pun mulai memainkan perannya di jalur maritim tersebut.
Putuhena mengatakan, Turki memosisikan diri sebagai pemimpin sekaligus pelindung Dunia Islam. Adapun Portugis bermaksud sebaliknya, yakni ingin meneruskan Reconquista yang bermakna menghancurkan Islam sekaligus merebut wilayah muslim.
Setidaknya sejak 1500, para saudagar nusantara sudah lebih aktif berperan dalam perdagangan dengan dunia luar. Hal itu terbukti dari kesaksian Lewis Barthema dari Roma. Pada 1503, Barthema yang berhasil memasuki Makkah dengan menyamar sebagai seorang muslim mencatat kehadiran jamaah haji asal Anak Benua India dan Lesser East Indies (Nusantara).
Portugis kemudian terus memblokade pergerakan kapal-kapal Aceh yang hendak mencapai Arab. Namun, upaya kerajaan Kristen itu tak selalu berhasil. Suatu sumber dari Venesia menyatakan, pada 1565 dan 1566 terdapat lima kapal dari kesultanan Aceh yang berlabuh di Jeddah.
Semangat Reconquista membuat Portugis terlampau fokus pada upaya memusuhi Islam secara terbuka. Itulah yang membedakannya dengan Belanda. Belanda lebih mementingkan perniagaan, alih-alih Kristenisasi, selama berada di nusantara. Portugis pun kalah saing dalam merebut pasaran perdagangan sekaligus menanamkan pengaruh di nusantara.
Memasuki abad ke-17, kekuatan Portugis mulai memudar. Pada saat yang sama, Turki juga kehilangan kendali atas jalur perdagangan Nusantara-Arab. Sejak saat itu, Belanda dan Inggris-lah yang lebih mendominasi.
M Dien Majid dalam Berhaji di Masa Kolonial menerangkan, jamaah haji Nusantara pada abad ke-17 umumnya menumpangi kapal-kapal dagang milik orang Arab atau India. Kebanyakan armada itu berlabuh di Temasek (Singapura) atau Penang sehingga mereka harus menuju ke sana terlebih dahulu. Di kedua tempat itu, sudah terdapat kapal-kapal khusus semacam embarkasi bagi jamaah haji.
Secara keseluruhan, perjalanan haji pada masa itu bisa memakan waktu tiga hingga empat tahun.
Akan tetapi, calon jamaah kerap menghabiskan waktu di daerah sekitar embarkasi untuk menambah uang dan bekal. Tak sedikit dari mereka yang bersedia menjadi pekerja perkebunan di Singapura dan Penang, baik sebelum ataupun sepulangnya dari menunaikan rukun Islam kelima itu.
Zaman Kolonial
Sejak abad ke-18, dominasi Belanda kian menguat di seluruh wilayah nusantara. Calon jamaah haji dipersulit dengan adanya berbagai peraturan (besluit) sepihak yang dilancarkan Kompeni. Misalnya, aturan tertanggal 4 Agustus 1716 yang melarang kapal-kapal Belanda untuk mengangkut jamaah haji.
Alhasil, para calon tamu Allah itu harus menumpangi banyak kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya hingga berhasil keluar dari wilayah Hindia Belanda. Untuk selanjutnya, mereka menuju Jeddah dengan melalui beberapa pelabuhan di pesisir India atau Hadramaut (Yaman).
Pada permulaan abad ke-19, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dinyatakan bangkrut. Nusantara pun mulai dikuasai secara langsung oleh Negeri Belanda. Namun, pelayaran haji sempat terbebas dari kendali langsung Belanda.
Sebagai contoh, pada 1825 untuk pertama kalinya Muslim Nusantara menggunakan kapal khusus pengangkut jamaah haji. Kapal itu disediakan seorang saudagar melayu bernama Syekh Umar Bugis. Sejak saat itu, musim haji dianggap sebagai momen bisnis yang menguntungkan.
Inggris pun tertarik untuk ikut menarik keuntungan dari bisnis haji. Pada 1858, perusahaan Britania Raya menggunakan kapal uap untuk mengangkut jamaah haji nusantara dari Batavia (Jakarta). Inilah untuk pertama kalinya Muslim Indonesia berangkat haji dengan menumpangi kapal uap. Waktu tempuh dari Nusantara ke Arab pun menjadi lebih ringkas ketimbang dengan kapal layar. Hanya perlu 20 atau 25 hari untuk bisa sampai di Jeddah
Sebagai perbandingan, dahulu ketika kapal layar masih menjadi andalan, jamaah haji nusantara tidak bisa langsung sampai di Arab, tetapi harus singgah terlebih dahulu di banyak lokasi. Katakanlah, mereka berangkat dari Aceh, maka mesti berlabuh di India. Dari India, mereka kemudian mencari kapal lain yang hendak berlayar menuju Hadramaut (Yaman) atau Jeddah. Semua itu tentunya memakan waktu berbulan-bulan.
Langkah korporasi Inggris itu diikuti berbagai pebisnis lainnya dari India, Singapura, atau Arab. Pesatnya persaingan bisnis itu membuat orang-orang yang hendak berhaji mencari celah agar dapat berhemat.
Untuk mengurangi biaya transportasi, sekelompok keturunan Arab di Batavia menggalang dana bersama. Mereka kemudian membeli kapal dari Basier en Jonkheim. Armada tersebut dapat membawa 400 orang jamaah haji sekali jalan dari Batavia, ke Padang, hingga Jeddah.
Terusan Suez dibuka pada 1869. Sejak saat itu, bisnis pelayaran menjadi begitu bergairah. Pemerintah kolonial Belanda pun ikut-ikutan dalam usaha transportasi perjalanan haji nusantara.
Setahun setelah Konsulat Belanda berdiri di Jeddah pada 1872, Belanda mengadakan perjanjian kontrak dengan tiga perusahaan pelayaran, yaitu Rotterdamasche Llyod, Mij Nederland, dan Mij Oceaan. Korporasi itu belakangan dikenal sebagai Kongsi Tiga.
Bagaimanapun, jamaah haji Nusantara cenderung bersikap dingin terhadap Belanda. Apalagi, rezim kolonial itu kerap mengeluarkan berbagai aturan yang menyulitkan perjalanan haji. Alhasil, banyak calon tamu Allah itu yang lebih memilih Singapura atau Malaya sebagai embarkasi haji, alih-alih Batavia.
Mulanya pada 18 Oktober 1825. Itulah untuk pertama kalinya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan terhadap haji. Beleid itu termuat dalam surat rahasia yang diedarkan kepada para pejabat kolonial hingga level perdesaan.
Isinya, mengharuskan tiap calon jamaah haji untuk memiliki paspor ibadah haji. Selain itu, ongkos naik haji juga ditetapkan sebesar f 110. Bila menghindar, seorang haji akan dikenakan denda dua kali lipat begitu kembali ke Tanah Air.
Putuhena menjelaskan, aturan tersebut didasari kekhawatiran Belanda terhadap kian bertambahnya jumlah jamaah haji asal nusantara dari tahun ke tahun. Mereka cemas bila para haji membawa gagasan Pan-Islamisme sepulangnya dari Makkah, untuk kemudian menginspirasi gerakan perlawan terhadap rust en orde atau tatanan kolonial.
Agar tak dituding memetik untung dari haji, pemerintah berdalih, dana sebesar f 110 itu diperuntukkan bagi kepentingan masjid wilayah masing-masing. Namun, rakyat umumnya merasa terganggu dengan adanya peraturan demikian.
Erlita Tantri dalam artikelnya, Hajj Transportation of Netherlands East Indies 1910-1940 menjelaskan, para calon jamaah haji nusantara pada zaman kolonial dapat menentukan dari titik mana mereka akan memulai perjalanan ibadahnya. Setidaknya, ada tiga pilihan utama.
Pertama, mereka dapat menggunakan kapal-kapal milik perusahaan Belanda yang berangkat dari pelabuhan-pelabuhan besar nusantara, seperti Batavia. Kedua, mereka pergi terlebih dahulu ke Singapura, Penang, atau Malaya karena di ketiga tempat itulah terdapat embarkasi haji yang terbuka bagi orang luar koloni Inggris. Selanjutnya, mereka menaiki kapal milik perusahaan Britania Raya.
Ketiga, mereka menumpangi kapal laut jarak jauh yang menuju Bombay atau Suez. Dari sana, barulah mereka berlayar ke Jeddah, untuk selanjutnya Madinah dan Makkah.
Dari laut ke udara
Begitu besar antusiasme orang Indonesia demi bisa memenuhi panggilan berhaji, bahkan sejak zaman penjajahan. Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan pada 1941, pada 1878 (dengan kapal layar) jamaah haji Indonesia tercatat sekitar 5.331 orang. Setahun kemudian atau pada 1880, jumlah itu menjadi 9.542 jamaah. Artinya, naik hampir dua kali lipat.
Perbandingannya dengan jamaah dari negeri-negeri lain juga terbilang besar. Pada 1921, ada sebanyak 28.795 jamaah haji asal Hindia Belanda. Itu setara 47,3 persen dari total jamaah haji seluruh dunia pada tahun itu, yakni sebanyak 60.786 orang.
Bahkan, saat resesi ekonomi pada 1928 jamaah haji Nusantara justru meningkat menjadi 28.952 dari 52.412 orang jamaah seluruh dunia. Hingga 1930-an, jamaah haji Indonesia berjumlah di atas 39 ribu orang.
Pada zaman Jepang, tak diketahui secara pasti jumlah jamaah haji Indonesia. Apalagi, pada zaman mempertahankan kemerdekaan, periode 1945-1948. Perang menjadi alasan tiadanya statistik yang memadai untuk itu.
Henri Chamber-Loir dalam Naik Haji di Masa Silam mengatakan, segera setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Republik Indonesia pun mulai membenahi berbagai macam urusan dalam negerinya, termasuk terkait soal keagamaan. Kementerian Agama ketika dinakhodai KH A Wahid Hasyim meletakkan beberapa dasar kebijakan di bidang perhajian.
Pada Desember 1949, Muktamar Kongres Muslimin Indonesia diikuti delegasi dari 156 organisasi Islam di Yogyakarta. Salah satu hasil forum itu ialah pembentukan Yayasan Panitia Haji Indonesia (PHI) yang akhirnya resmi didirikan pada awal 1951. Yayasan itulah yang kemudian ditunjuk Kemenag sebagai pengatur, penyelenggara, sekaligus pengawas perjalanan jamaah haji –di samping adanya peranan pemerintah pusat.
Waktu itu, negara baru saja keluar dari perang mempertahankan kemerdekaan. Alhasil, devisa cukup terbatas. Untuk mencegah keluarnya devisa secara besar-besaran, maka jumlah jamaah haji pun dibatasi, yakni tak boleh melampaui 10 ribu orang. Pendaftaran haji pun diatur dengan sangat ketat.
Menurut Prof Budi Sulistiono dalam Ibadah Haji dan Tradisi Budaya Sosial (2018), kapal laut masih menjadi alat transportasi andalan untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Bahkan, kondisi itu tetap bertahan meskipun moda pesawat terbang sudah mulai dipakai sejak 1952 demi melayani jamaah haji Indonesia.
Memang, calon jamaah mesti mengeluarkan biaya lebih mahal untuk dapat menumpangi burung besi. Waktu itu, ongkosnya mencapai sekitar 17 ribu per orang. Besaran tersebut lebih dari dua kali lipat tarif kapal laut kala itu, yakni 7.500. Wajar bila jalur laut masih menjadi primadona.
Pada 1952, calon jamaah haji asal Indonesia yang menggunakan kapal laut tercatat sebanyak 14.031 orang, sedangkan via pesawat terbang sebanyak 293 orang. Padahal, perjalanan laut bisa memakan waktu tiga bulan lamanya. Tak jarang pula ada calon jamaah yang wafat di atas kapal, sebelum tiba di Tanah Suci.
“Pengalaman ini tak dirasakan oleh jamaah haji setelah tahun 1979. Sebab, kapal-kapal pengangkut calon jamaah haji dari Indonesia terakhir kali beroperasi pada tahun itu,” tulis guru besar ilmu sejarah kebudayaan Islam itu. (*)